Belakangan ini, hidup sedang tidak baik-baik saja. Terutama, memasuki tahun 2022 ini. Saya baru promosi bulan Mei tahun lalu, namun hak yang seharusnya saya dapatkan dari tahun lalu masih tertahan karena peraturannya masih digodok hingga sekarang. Pada awalnya saya santai saja karena saya yakin hak saya akan cair di waktu yang tepat. Namun belakangan ini, perasaan cemas itu akhirnya mulai menghantui, karena sudah hampir setahun belum ada kejelasan juga tentang kapan hak saya itu bakal turun, padahal beban kerja dua kali lipat daripada sebelumnya dan tentu saja seiring dengan itu, intensitas stres makin bertambah. Padahal, saya menyukai pekerjaan saya yang baru: sangat menantang dan memaksa saya untuk terus belajar memahami hal-hal yang sebelumnya terasa sulit. Di sisi lain, kebutuhan pribadi mulai membludak, sudah beberapa bulan terakhir ini saya sangat-sangat menahan diri untuk membeli apa yang saya inginkan dan hidup lebih layak, sekadar untuk menabung demi masa depan dan kebutuhan di usia segini yang makin banyak. Akhirnya, saya lebih sering mengurung di kamar, jarang sekali SKSD atau ngopi bareng teman yang biasa saya lakukan sebelumnya, kecuali untuk olahraga. Intensitas olahraga pun berkurang jauh, karena tiap pulang kantor sudah dalam keadaan tepar, tidak ada tenaga tersisa untuk sekadar menggerakan kaki mengelilingi lapangan atau danau. Penempatan kantor yang sekarang pun lumayan memengaruhi kondisi saya setahun terakhir ini, karena jauh dari mana-mana dibanding dengan kantor yang lama. (update: April 2022 hak saya sudah cair.)
Satu-satunya hal yang membuat saya bisa bertahan adalah pasangan saya, di samping keluarga juga. Dia adalah pasangan sekaligus sahabat saya. Saya tidak pernah kehabisan topik untuk mengobrol dengan dia. Dan kesedihan itu bisa dengan cepat berubah menjadi senang lagi setelah mengobrol dengannya. Hidup menjadi lebih mudah ketika dilalui bersama dia. Namun, saat ini dia sedang berduka. Dua kucing kesayangannya mati di waktu yang berdekatan karena diserang virus mematikan, namanya Swirly dan Kimmy. Dia sangat-sangat terpukul dengan kejadian itu. Beberapa hari terakhir obrolan kami adalah tentang mengenang bagaimana kucing-kucing itu bagaikan malaikat kecil bagi dia. Dan Swirly dan Kimmy adalah kucing liar yang memilih pasangan saya sebagai majikannya. Tidak ada ikatan yang lebih kuat dibanding manusia dan hewan peliharaan yang mereka selamatkan sebelumnya. Swirly adalah kucing favoritnya pasangan saya, karena dia periang dan suka bermain dengan kucing-kucing lainnya. Dia penyayang dan tidak punya musuh. Kimmy adalah kucing kecil polos yang lumayan penakut, namun sejak ada Swirly dia jadi tidak penakut lagi dan jadi kucing periang. Bisa dibayangkan bagaimana kehilangan dua kucing dalam waktu dua hari menimbulkan efek yang seperti apa ke pasangan saya yang memiliki sifat sangat lembut dan penyayang itu. Dia berkali-kali bilang bahwa kematian dua kucing itu adalah kesalahan dia karena tidak buru-buru memberi vaksin ke mereka. Saya berkali-kali menenangkan dan bilang bahwa dia tidak salah, karena dokter sekalipun setelah mengecek kondisi kucing tersebut tidak ada virus yang berbahaya di tubuh mereka, yang belakangan diketahui diagnosis itu salah setelah kedua kucing itu sedang sekarat, tubuhnya direnggut virus mematikan yang bernama calici.
Namun, yang namanya grief, atau berduka, memang tidak semudah satu obrolan dua obrolan langsung selesai, langsung, deh, bisa berdamai dengan keadaan. Berduka adalah sesuatu yang kompleks, sesuatu yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Luka yang ditorehkan duka terlalu dalam, mustahil bisa sembuh dalam waktu singkat. Dan ketika itu terjadi, peran orang-orang terdekat sangatlah penting dalam proses penyembuhan luka tersebut. Saya, sebagai orang terdekatnya dia mencoba untuk tetap terus mendukung dia. Di sisi lain, luka yang diakibatkan terlalu dalam, ditambah kami yang sedang menjalani hubungan LDR sehingga proses itu jadi semakin sulit. Pada akhirnya ketika langit-langit sudah terlalu buram untuk bisa melihat sepercik cahaya harapan, saya bilang ke dia bahwa mungkin hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Sebuah pernyataan yang bahkan saya pun tidak yakin akan kebenarannya. Apakah waktu bisa menyembuhkan? Atau sebenarnya, memang tidak ada sesuatu hal pun di dunia yang bisa menyembuhkan luka dari duka?













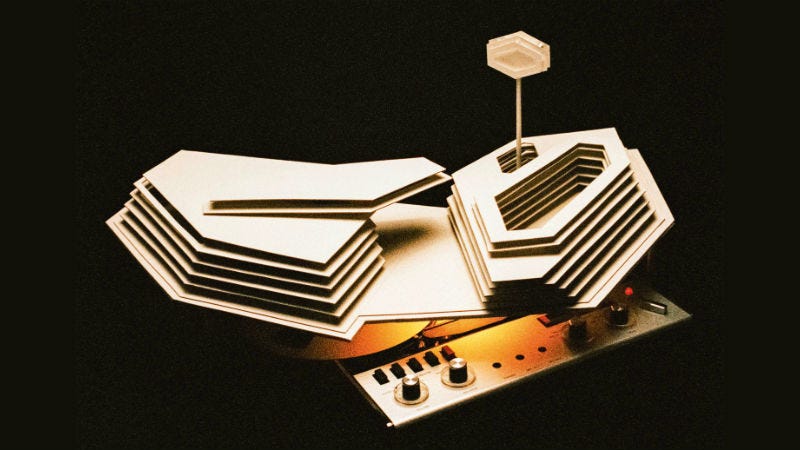












.jpg)



